Islam dan Demokrasi: Suatu Nisbah
Dua catatan penting perlu disampaikan. Pertama, Islam dan demokrasi tak bisa dibandingkan dalam satu level karena Islam bukan melulu kekuatan politik. Demokrasi tidak memiliki aspek-aspek seperti cult, creed, code, dan community. Demokrasi bukanlah agama dan hanya masuk dalam bagian kecil sistem kepercayaan Islam. Kedua, demokrasi tak punya arti yang secara definitif disepakati bersama. Akibatnya, Islam pun bisa memberi pengertian atau isi kepada demokrasi seturut pemahaman Islam. Kalau begitu, Islam juga berhadapan dengan institusi lain yang juga punya kans untuk memberi penafsiran atas demokrasi.
Dua catatan itu menjelaskan bahwa Islam dan demokrasi bukan dua entitas yang bisa dipertentangkan secara ekstrem atau diletakkan dalam satu blok. Di satu sisi bisa dikatakan demokrasi cocok dengan Islam, tetapi di lain sisi, kompatibilitas itu ada dalam batas-batas tertentu. Islam tetap punya aspek yang memberi kesan tidak cocok dengan demokrasi.
Islam versus Demokrasi
Ada pola relasi subordinatif dalam paradigma Islam. Misalnya, Islam memahami diri sebagai substansi mutlak dan negara menjadi medium bagi Islam untuk mewujudkan nilai-nilai perenial (Nurcholish Madjid, op.cit.). Islam menjadi tujuan dan negara adalah sarana. Padahal, demokrasi hanyalah satu dari sekian peranti tata kelola negara. Maka, demokrasi pun hanyalah sarana. Islam punya kompleksitas sistem pemikiran sehingga bisa memberi kerangka yang lebih komprehensif terhadap demokrasi. Hal ini akan menempatkan demokrasi di hadapan hukum dan ajaran Islam. Artinya, demokrasi dihadapkan pada teologi Islam dan aspek teologis Islam menjadi otoritas tertinggi untuk mengevaluasi demokrasi, yang mesti menyesuaikan diri dengan “jiwa dari hukum yang diwahyukan” (Maulana Muhammad Ali, 1996). Di sini ada perbedaan esensi. Demokrasi sebagai olah pikir manusia membuka peluang bagi perubahan masyarakat dan bisa saja perubahan itu merongrong nilai abadi dalam Islam (Ahmad Suaedy, 1994).
Di sinilah letak potensi pertentangan antara Islam dan demokrasi, yaitu ketika gagasan teologis dalam Islam berhadapan dengan gagasan demokrasi. Kasus Mahmud Mohamed Taha (yang dihukum gantung karena menyuarakan hak untuk berpindah agama) bisa jadi contoh jelas untuk menggambarkan betapa institusi keagamaan, biar bagaimanapun, memiliki sistem kepercayaan yang bisa bertentangan dengan gagasan demokrasi (Ahmad Suaedy, op.cit.).
Demokrasi Islami
Karena demokrasi tidak memiliki definisi mutlak yang disepakati bersama, Islam berpeluang memberi pemaknaan atau warna Islam kepada demokrasi. Barangkali mirip dengan upaya bank-bank syari’ah. Dalam hal ini bisa dipahami bahwa syari’ah demokratis menjadi deep driving force yang menentukan pola tingkah laku manusia. Demokrasi tidak dipandang sebagai ‘budaya’ luar (Barat misalnya) tetapi memang secara internal ada dalam Islam sehingga harus diwujudkan seturut syari’ah Islam. Ini bisa diberi atribut: demokrasi syari’ah atau demokrasi Islami.
Dalam hal ini, demokrasi bukan kutub lawan Islam. Kalau ada konflik pun, hanya akan memposisikan demokrasi sebagai medium antara Islam dan kekuatan politik lainnya. Ini bisa dilihat dalam pergumulan Islam dengan kekuatan militer di Indonesia (Douglas E. Ramage, op.cit.). Demokrasi menjadi ajang pergulatan penafsiran antara aspek teologis Islam dan aspek kekuatan-kekuatan politik lainnya. Jadi, konfliknya bukan antara Islam dan demokrasi, melainkan Islam dan kekuatan politik lainnya.
Secara historis Islam sendiri memiliki tradisi yang menunjukkan ciri-ciri demokratis. Keadaan bahwa kepemimpinan ditetapkan atas dasar prestasi, proses pemilihan terbuka, hak dan kewajiban rakyat yang sama, pengakuan hak pada golongan agama lain, menunjukkan keunggulan Islam sebagai kekuatan politik yang luar biasa pada masanya (Nurcholish Madjid, op.cit.). Ini adalah gambaran bagaimana Islam mewujudkan demokrasi. Ada peluang bagi suatu Islam demokratis.
Islam Demokratis: Suatu Antisipasi
Potensi konflik Islam dan demokrasi terletak pada penafsiran terhadap dua substansi tersebut. Memang menyebut Islam berarti menunjuk unsur teologis, sedangkan demokrasi mengacu pada sistem ‘sekular’ yang tanpa gagasan teologis pun bisa bertahan juga. Jika keduanya dibatasi secara kaku malah bisa terjadi kontradiksi antara Islam dan demokrasi (John L. Esposito & John O. Voll, 1996).
Demokrasi memang merangsang aneka pertanyaan filosofis untuk menentukan batasan-batasannya (Ross Harrison, 1993). Kerumitan titik pijak diskusi demokrasi ini mengesankan bahwa demokrasi tak bisa diidentikkan dengan atribut entah Barat, Kristen, atau sekular. Sekali lagi, sebagai prinsip dasar cukuplah diterima bahwa demokrasi ialah perimbangan politik. Dalam pelaksanaannya, variasi terjadi sehingga tak bisa ditentukan model demokrasi yang akurat. Dengan begitu, Islam bisa berinteraksi dengan demokrasi. Akan tetapi, interaksi itu akan stagnan jika Islam sendiri ditafsirkan secara kaku. Dialog Islam dan demokrasi akan mengalami kebuntuan jika teologi Islam sendiri tidak mengalami transformasi. Ini bukan lantaran demokrasinya statis, melainkan perumusan kembali identitas Islam macet, atau teologinya tak berkembang.
Masa depan Islam sedikit banyak dipengaruhi oleh bagaimana teologi Islam memaknai arus kemajuan atau perkembangan. Maka, Islam perlu mengupayakan teologi transformatif demi memberi ruang kebebasan yang dibutuhkan untuk menanggapi perkembangan zaman (Muhammad AS Hikam, 1996). Islam perlu merumuskan pandangan terhadap sekularisasi, martabat manusia, solidaritas, dan kerja sama antaragama, misalnya. Akan tetapi, juga diperlukan keterbukaan pada syari’ah yang sewajarnya: sumber-sumber syari’ah perlu dilihat secara proporsional. Misalnya, aspek historis perlu dipertimbangkan juga supaya bisa ditemukan nilai mana yang sungguh-sungguh bersifat perenial dan mana yang lebih spasial dan temporal (Djohan Effendi & Ismed Natsir, 1981). Dengan begitu, bisa dipilah-pilah mana yang mutlak dan relatif sehingga tak ada pemutlakan antara keduanya (yang cenderung menimbulkan ciri ideologis dalam Islam).
Usaha ini akan menghindarkan Islam dari bahaya stagnasi dan arogansi sebagaimana pernah dialami oleh lembaga Gereja Katolik. Sebut saja salah satu gagasan teologisnya yang seringkali dijadikan contoh landasan kemandegan Katolik, yaitu gagasan extra ecclesiam nulla salus (di luar Gereja tak ada keselamatan). Rumusan semacam ini sempat memandulkan Gereja sebelum Gereja lambat laun melakukan tafsir ulang terhadap gagasan-gagasan dasar teologis maupun gagasan-gagasan dasar sekularisasi dunia.
Usaha reinterpretasi terhadap Islam atau teologi transformatif juga akan memantapkan kekuatan politis Islam. Secara teoretis dapatlah disimpulkan bahwa Islam tetap memandang demokrasi sebagai bagian penting peradaban manusia (Arief Afandi, 1997). Islam dan demokrasi tak terpisahkan, sebagaimana doktrin Islam menunjuk adanya keterkaitan kuat antara Islam dan negara. Karena itu, secara teoretis hubungan Islam dan demokrasi tak pernah dicemaskan. Relasi antara Islam dan demokrasi juga lebih bersifat positif. Setidak-tidaknya, syari’ah demokratis lebih menonjol jika dibandingkan dengan syari’ah nondemokratis (Fahmy Huwaydi, 1996). Itu secara teoretis. Bagaimana praktiknya?
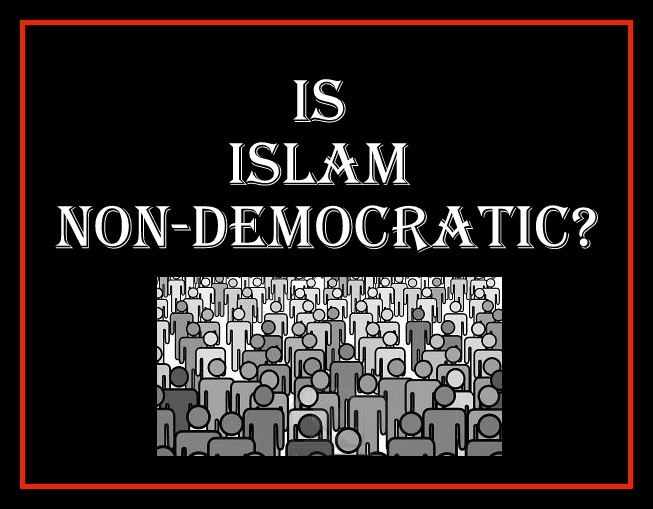
2 responses to “Syari’ah Demokratis (2)”
[…] Read more… […]
LikeLike
[…] secara teoretis bisa ditunjukkan relasi positif antara Islam dan demokrasi, tidak selalu demikian halnya jika sisi politik praktis dipertimbangkan. Kadang kala yang lebih […]
LikeLike