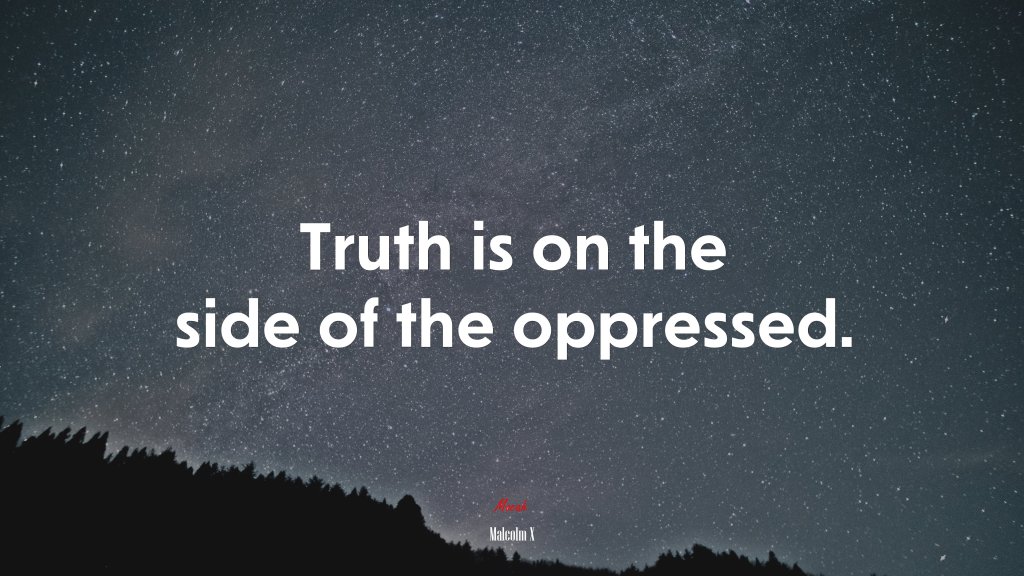Katanya, Tuhan itu selalu bersama manusia. Trus, kalau manusia berdosa, di manakah Tuhan? Tidakkah Dia juga berdosa bersama manusia yang berdosa itu tadi?
Begitu pertanyaan yang masuk ke telinga saya hari ini. Menarik memang untuk yang gemar utak atik otak. Akan tetapi, di balik pertanyaan itu ada dikotomi antara Tuhan dan manusia, seakan-akan ada dua objek yang gandengan dan kalau salah satu objek ini korupsi, objek yang digandengnya juga tersangkut korupsi alias ikut jadi koruptor juga.
Teks bacaan hari ini membongkar asumsi dikotomis di balik pertanyaan tadi; tapi, kalau mau utak-atik-otak saja, wacana tadi bisa dikoreksi dengan melihat pengertian ‘dosa’-nya sendiri sih: bukankah dosa itu tak lain adalah tindakan memisahkan diri dari kesatuan dengan Tuhan? Bukankah dosa itu hanyalah kata lain dari tindakan penyangkalan ikatan manusia dan Tuhannya? Dengan kata lain, bukankah sebetulnya dosa itu sendiri merepresentasikan ulah manusia untuk meninggalkan Tuhan?
Menariknya, Tuhan itu seperti Kebenaran, yang begitu kuat sehingga kita bisa menyangkalnya (dengan paham ateisme, misalnya) baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain, tetapi entah baik atau buruk tindakan kita, Dia tak akan meninggalkan kita; ia tetap tinggal di sana, bersembunyi dalam hati kita. Dengan begitu, tidak perlulah kiranya mempersoalkan apakah Tuhan jadi ikut berdosa saat manusia bertindak dosa.
Dalam teks bacaan hari ini, sifat relasional Allah-manusia ditampakkan dalam compassion Yesus: hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kata kerja yang dipakai di situ konon ada 12 kali dalam seluruh teks Injil dan hanya dilekatkan pada Allah dan Yesus; seakan-akan hanya Allah dan Yesus ini yang punya kekuatan untuk mewujudkan compassion. Akan tetapi, teks hari ini persis menegaskan bahwa kapasitas itu juga diberikan kepada manusia lain yang menerima panggilan-Nya, Manusia lain ini tak pernah bisa dibatasi pada afiliasi agama tertentu. Akan tetapi, kalau sudah nyangkut-nyangkut agama begini, segala hal bisa jadi runyam karena bisa jadi manusianya malah berfokus pada agama per se alias agamanya sendiri dan malah mengabaikan Tuhan atau Kebenarannya.
Lagi-lagi dikotomi ini, bukan?
Njuk gimana biar gak dikotomis dong? Ya dengan mengakui bahwa Kebenaran Mutlak itu tak bisa diklaim atau direduksi atau dikungkung oleh satu lembaga, apalagi satu orang tertentu. Maka, para pengklaim Kebenaran mesti menjalin relasi untuk menguak Kebenaran yang bersembunyi dalam hati setiap orang. Relasi itu bisa memuat konflik juga, tetapi konflik itu malah bisa jadi cara untuk mengasah atau mempertajam intuisi manusia terhadap Kebenaran, yang mesti di ujung sana diverifikasi dengan kemuliaan hidup bersama.
Dalam konflik itu, bisa jadi ada pihak yang powernya jauh lebih kuat, dan jika yang kuat ini menunjukkan kekuatannya dengan menindas yang lemah, tampaknya Kebenaran jadi samar-samar di situ. Jika agama sedemikian kuatnya sehingga penganutnya malah jadi terpaksa menganutnya, kebenaran agama itu jadi rapuh. Begitu seterusnya, jika orang bebas menganut agamanya dan memaksakan orang lain menganutnya, Kebenaran juga jadi samar-samar. So, Kebenaran malah terkuak kalau orang melihat dari sudut pandang pihak yang dipaksa atau ditindas, sebagai suatu challenge terhadap apa yang sudah dianggap mapan atau fixed atau established. Begitu gak sih?
Tuhan, mohon rahmat supaya kami mampu mengaktualkan sifat-Mu, yang pengasih lagi penyayang. Amin.
HARI MINGGU BIASA XI A/1
18 Juni 2023
Kel 19,2-6a
Rm 6,5-11
Mat 9,36-10,8