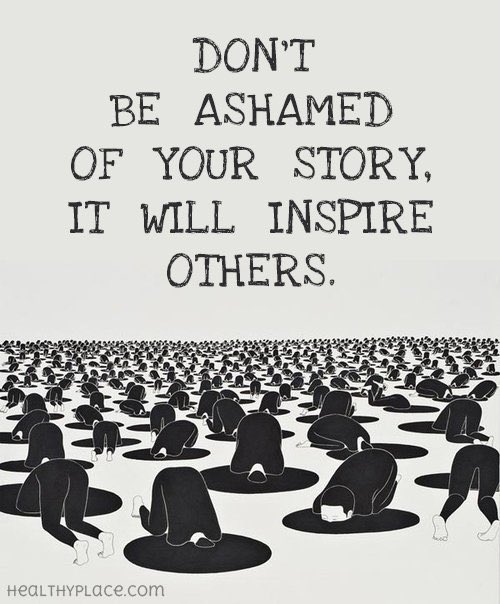Sampai saat ini, di negeri yang konon sudah merdeka, masih ada orang yang hidupnya jadi lebih rumit bukan karena ia malas atau tidak qualified, melainkan semata karena stigma. Saya ingat betul ketika suatu dini hari bersama beberapa teman menyeberang dari Hong Kong ke Macau dalam kondisi belum tidur sejak dini hari sebelumnya. Di Hong Kong Macau Ferry Terminal saat itu, bahkan kami tak bisa hanya untuk sekadar menyelonjorkan kaki di selasar kios-kios yang sudah tutup atau belum buka itu. Ada polisi yang berkeliling dan meminta kami berdiri, sekurang-kurangnya itulah tafsiran kami dari isyarat tangannya. Bahkan, sesampai di Macau, paspor kami semua dikumpulkan dan kami menunggu di luar; tidak ada tempat untuk duduk, dan niat untuk selonjoran di halaman terminal nan sunyi sepi itu mesti kami urungkan.
Diam-diam saya curi pandang ke arah ruang petugas imigrasi yang hanya ada beberapa orang sampai curi pandang itu dicuri kembali oleh para petugas itu. Mereka tidak melakukan apa-apa terhadap paspor kami, hanya sesekali melihat ke arah kami. Itu berlangsung hampir satu jam, dan kami menduga bahwa perlakuan ini tampaknya terhubung dengan kasus bom Bali. Baiklah, kami tidak begitu menderita bahkan jika stigma teroris itu dilekatkan pada jidat kami. Mungkin ini namanya menanggung kelemahan sesama, wkwkwkwk.
Menariknya, ketika saya memisahkan dari sekadar untuk walking meditation, saya mendengar sapaan dalam bahasa Jawa tetapi suara penuturnya tidak saya kenal. Bukan salah satu dari teman saya dan memang kurang terasa medhok alias aksen Jawanya tak terdeteksi. Karena sapaannya ini memakai ungkapan Jawa halus, saya pun menanggapinya secara halus. Saya tak bisa menyembunyikan ketercengangan saya. Yang menyapa saya ini tampaknya seorang polisi karena saya lihat ada pentungan di samping pinggangnya.
Lah, bukannya hansip ya, Mo?
Oh iya ya, hansip aja deh, tapi seragamnya lebih keren sih.
Kepo saya membuat polisi hansip ini lebih banyak omong; dan sebenarnya saya cuma penasaran bagaimana orang ini, warga negara di situ, bisa memakai bahasa Jawa. Tidak ikut kursus, tidak kelihatan kebantulan, kesoloan, ketegalan, atau keklatenannya. Ternyata, polisi hansip yang kelihatan seumuran dengan paman saya [yang seumuran dengan dia] ini berada di Macau sejak tahun 60-an. Persisnya, ini adalah pelarian dari Indonesia ketika pembikin Orde Baru memakai stigma PKI. Polisi hansip ini hanyalah secuil korban stigma PKI, yang tentu tidak hanya kesulitan untuk duduk selonjor. Barangkali, korban stigma PKI yang tidak bisa kabur ke Macau dan terpaksa tinggal di NKRI memiliki jalan hidup yang lebih rumit lagi.
Stigma memang bisa mengerikan, dan saya pikir, stigma yang paling mengerikan adalah stigma yang berbasis agama. Kenapa? Karena stigma ini bisa dilekatkan bahkan terhadap orang yang sudah mati sekalipun. Bayangkan, orang yang sudah mati pun bisa jadi bahan perseteruan mengenai bagaimana dia mesti dikuburkan!
Kalau Anda melihat film Kingdom of Heaven, pada adegan awal ditunjukkan bagaimana stigma pendosa membuat kepala orang mati pun tak layak tetap sambung dengan badannya. Kalau Anda memperhatikan film Luther, Anda dapat melihat bagaimana stigma terhadap orang yang bunuh diri menyembunyikan atau melanggengkan ketidakadilan dalam struktur Gereja (orang putus asa karena gak kuat bayar pajak Gereja lantas bunuh diri lalu divonis tak layak menerima pelayanan rohani). Kalau Anda melihat keadaan sekeliling saat ini pun, bisa jadi stigma religius masih hidup seiring kemajuan zaman. Saya masih mendapati misalnya orang yang berpindah agama dan hidupnya benar-benar seperti penderita kusta pada zaman Yesus, seakan-akan semesta mendukung hukuman ekonomi dan pengucilannya.
Teks bacaan hari ini bicara mengenai stigma yang berwujud salib, yang zaman now melekatkannya pada palang; jadi, palang merah, palang tiang jemuran, perempatan jalan, itu dianggap berbentuk salib. Padahal, salib yang dimaksud Yesus ‘hanyalah’ bagian horisontal palang yang dipanggul sampai pelaksanaan eksekusi mati; dan jika Anda simak salib Yesus ini, sebetulnya jelas bahwa eksekusi terhadapnya terjadi karena upaya pembaharuan yang dilakukannya membahayakan institusi politik dan agama; bukan cuma soal poligami. Tak mengherankan kalau Yesus menerima stigma subversif dan penistaan agama. Lalu, juga jadi jelas maksudnya bahwa “mengasihi orang tua lebih dari mengasihi Yesus” adalah soal orang mager dari status quo. Celakanya, mereka yang menggembar-gemborkan melawan status quo dengan slogan perubahan, bisa jadi justru hendak mempertahankan status quo.
Kok isa?
Ya bisa saja, karena yang hendak diubah bukan mentalitasnya, melainkan personalianya. Konon, tiada kawan-lawan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan. Itulah persoalannya: kepentingan abadi yang dimaksud itu mengabdi siapa dan berdampak ke mana? Kalau ujungnya bersifat sektarian, ya tetap saja status quo, cuma berganti (warna) kaos. Stigma agama sangat mungkin bersifat sektarian, yang malah tidak membebaskan manusia, tetapi menindasnya. Aparat religius secara lantang bisa menyerukan kebesaran Allah, tetapi lupa bahwa mereka bukanlah Allah dan malah takut kalau-kalau Allah tidak besar lagi mereka tidak bisa lagi menikmati status quo. Asudahlah.
Tuhan, mohon rahmat keberanian untuk membongkar aneka stigma yang menentang kasih sayang-Mu. Amin.
HARI MINGGU BIASA XIII A/1
2 Juli 2023