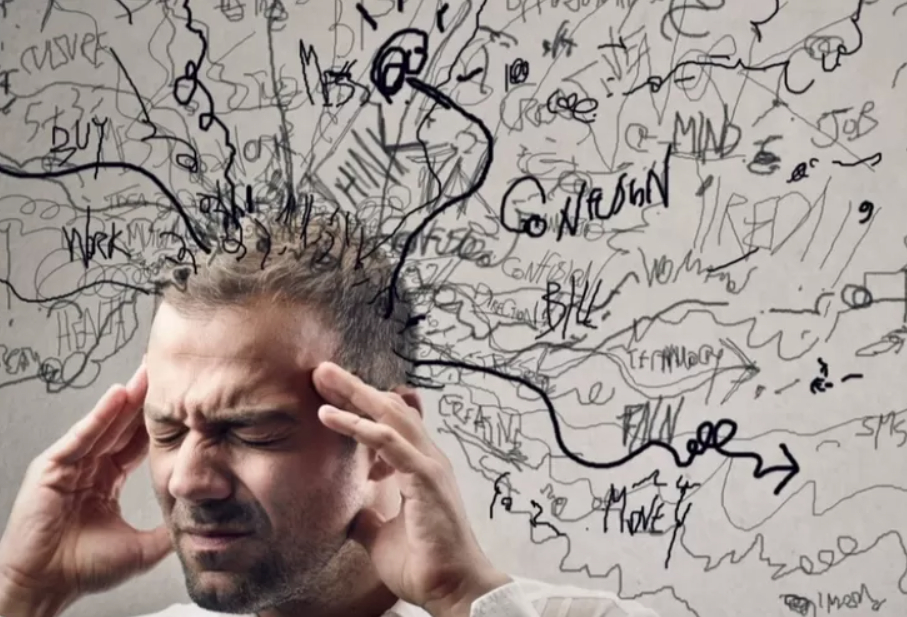Seorang teman menanyakan keadaan saya setelah hasil quick count keluar dan memunculkan akumulasi suara tertinggi untuk capres nganu; apakah saya kecewa atau sedih atau gimana. Saya jawab apa adanya sesuai pilihan kata yang disodorkannya: ada rasa kecewa dan sedih, tetapi segera saya tambahkan alasannya bukan karena capres nganu menang, melainkan karena ada yang suicide di tempat saya pasca coblosan.
Cecak tak tahu diri, dia kira di engsel pintu saya itu banyak nyamuknya po ya?
Selain itu, yang mungkin lebih penting, kecewa dan sedihnya muncul karena saya mesti koreksi apa yang saya pelajari dari proses tahun-tahun belakangan ini.
- Sebagian orang, seperti saya, mengira bahwa moral dan etika itu penting, tetapi sepertinya yang penting adalah “etika ndhasmu”. Suara penghuni kampus ya tak lebih dari suara para pelaku kejahatan, sama-sama dihitung satu suaranya. Jadi terserah kampus mau ngecipris apa, menarik hati orang miskin literasi (yang jumlahnya pasti jauh lebih besar), lebih berharga untuk coblosan daripada buang-buang waktu mendiskusikan program.
- Sebagian orang, seperti saya, membedakan kritik dari kebencian, bahkan mengira bahwa sejatinya kritik [alih-alih emang gua pikirin] justru adalah bagian dari cinta, tetapi tampaknya di negeri ini pembedaan seperti itu sangat langka. Adanya orang terbentur dulu baru kapok, itu juga kalau gak bebal.
- Sebagian orang, seperti saya, hanya memahami bansos sebagai tindakan karitatif/amal dalam kondisi darurat, tetapi tampaknya negeri ini membutuhkan orang melarat untuk sangu akhirat, maka perlu dirawat melaratnya. Outcomenya dobel: dapat suara elektoral, dapat surga akhirat.
- Tampaknya bansos lebih dibutuhkan dan lebih penting daripada keadilan sosial, bahkan meskipun yang belakangan ini dirumuskan sebagai bagian Pancasila.
- Sebagian orang, seperti saya, mengira bahwa kemajuan itu adalah perkara perkembangan kualitas hidup manusia, tetapi tampaknya lebih banyak yang meyakini bahwa kemajuan itu perkara wang sinawang modernitas dengan kiblat mancanegara.
Loh, berarti malah senang dong, Rom, dapat koreksian? Betul, koreksi itu mengembangkan. Saya senang, tetapi konsekuensi dari koreksi itu memberangus apa yang dalam sepuluh tahun terakhir ini saya tekuni setiap hari sebelum pandemi:
- Kalo memang etika itu gombal amoh atau mukiyo, untuk apa lagi omong soal agama, refleksi, diskusi? Ujung-ujungnya kan kalkulasi politik-ekonomi! Agama ya urus aja di altar, gak usah dibawa-bawa ke pasar!
- Kalo memang lebih banyak orang butuh bansos daripada keadilan sosial, njuk ngapain saya tiap hari baca teks suci, bikin konsiderasi, melihat koneksinya ke hidup sehari-hari dan ternyata itu dikepret aja dengan “etika ndhasmu” itu?
Lho, lha ya beda, Rom. Itu kan bekal sangu buat keselamatan kelak.
Ya itu persis masalahnya: kalau keselamatan kelak itu tak terhubung dengan moral dan etika sekarang di pasar juga, apa gunanya dibahas sekarang? Apa kalau sekarang sudah tahu etika yang datang dari agama, meskipun tak ada praktiknya, njuk itu cukup sebagai bekal mati masuk surga? Hidup “iman tanpa perbuatan”!
Jika begitu halnya, bisa dimaklumi orang rajin beribadat dan setelahnya meneruskan proyek galian singset tak ramah lingkungan, meneruskan izin proyek yang jelas bikin masalah dengan rakyat kecil (saya teringat warga korban Porong, Papua, Kalimantan, atau aneka lubang menganga di Belitung), dan nanti ibadat lagi dan terus suap trus korupsi, besoknya ibadat lagi, dan terus begitu, kan?
Ya ya ya, tapi itu adalah pikiran kotor sih. Agama punya dimensi yang mesti disimpan di altar, tapi juga ada yang bisa dan malah harus dibawa sampai pasar. Penghubung altar dan pasar itu namanya spiritualitas; sehingga spiritualitas bukanlah perkara bikin tanda salib atau membungkuk atau sujud dan seterusnya. Ke pasar gak harus bawa-bawa bendera, label, atau etiket agama; bisa-bisa runyam karena politik identitas (Ahok di 2017 bersinggungan dengan perkara macam begini).
Orang beragama atau menganut kepercayaan religius, ke pasar pun dia berspiritualitas dalam wujud etos kerja, juga moral dan etika. Itu sebabnya kalau di pasar adanya moral hazard, apa artinya sitir kitab suci dan bolak balik ziarah ke sana kemari? Hanya mereka yang miskin (niat) literasilah yang akan percaya bahwa bungkus suci itu sama dengan isinya, judul sama dengan content, penampakan sama dengan kenyataan, dan seterusnya.
Tampaknya 14 Februari 2024 adalah awal pertobatan yang sangat tepat untuk menyadari diri bahwa Anda dan saya minim literasi, dan saya akan berusaha mengendalikan diri untuk tidak bawa-bawa ayat suci.