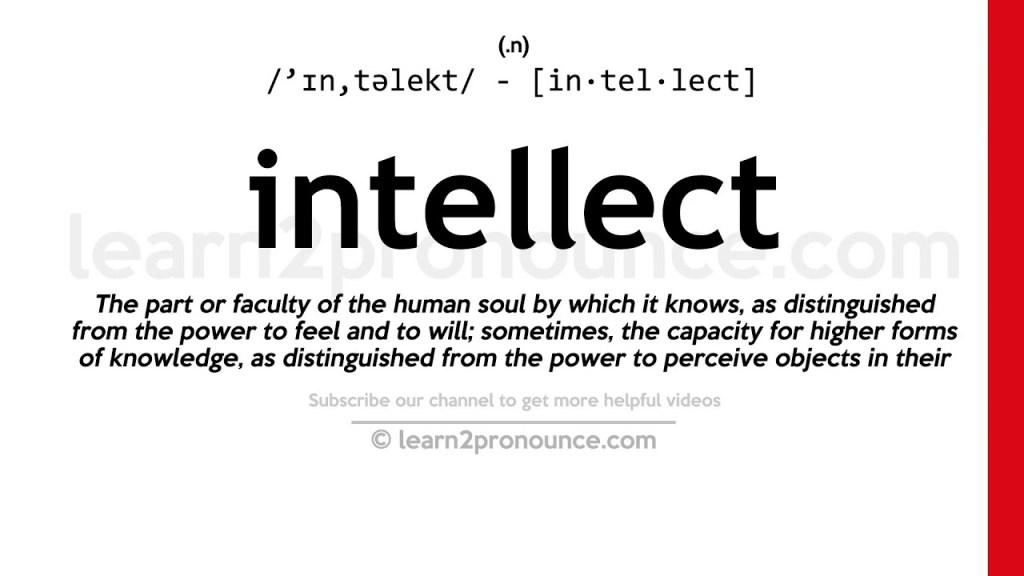Lebih dari tiga puluh tahun lalu, saya pulang kampung bersama setengah lusin adik kelas saya. Ada yang dari Cirebon, Bogor, Bekasi, Tangerang. Kampung saya sendiri ada di Jaksel, yang saya dengar beberapa waktu lalu kebanjiran setengah meter. Kami berencana naik bus dari satu kota ke kota lainnya. Tiba di Semarang, kami naik bus jurusan Cirebon. Belum ada penumpang lain, dan kami duduk seturut preferensi masing-masing. Tidak berapa lama, dari pintu depan ada beberapa lelaki masuk, saya menoleh ke belakang, tempat adik-adik saya duduk. Dari sana juga ada beberapa lelaki, kira-kira seusia dengan yang masuk dari depan, dan mungkin seumuran dengan om saya.
Yang dari depan mulai bicara menyebut soal karcis. Saya pikir, apa memang perlu beli karcis dulu ya, tetapi ini bukan bus eksekutif, bukan juga bus patas; mestinya tak perlu sangu karcis. Di situ saya mencium kecurangan pemilu, eh…. belum ya.
Saya tanya berapa harga tiketnya. Waktu itu, meskipun belum ada internet masuk desa, saya sudah tanya bapaknya Mbah Gugel dan harganya di kisaran delapan ribu rupiah. Lelaki yang rupanya pemimpin rombongan preman itu menyebut angka sepuluh ribu. Ya, itu di kisaran delapan ribu rupiah sih, cuma ini terlalu pagi serangan fajarnya. Bus baru saja tiba, dan tempat duduk kami juga belum terasa nyaman untuk bertelur. Belum ada penumpang lain yang naik.
Saya mulai mengendus unsur kekuasaan dan paksaan ketika lelaki itu mulai menyorongkan tangannya minta duit. Syukurlah, adik-adik saya tidak ada yang membangkang ketika saya ajak mereka turun. Artinya, mereka mesti bermanuver supaya bisa melewati laki-laki di pintu belakang.
“Loh, ini bagaimana, sudah duduk kok malah turun?” Rupanya lelaki tadi menyusul kami di pintu belakang bus.
“Ya kami tak punya duit segitu.” Saya tidak berbohong, cuma kan kelamaan kalau saya jelaskan bahwa dari Magelang ke Semarang kami alokasikan duit sekian, dari Semarang ke Cirebon sekian, dan seterusnya, kan?
“Ya sudah, maunya berapa?”
Nah, repot ini kalau saya sebut nominal sesuai perkiraan harga tiket busnya.
“Tiga ribu.”
Setelah saya sebut angka itu sambil jalan ke tempat tunggu bus, preman itu berteriak-teriak. Marah rupanya. Saya tidak mendengarkan caci makiannya kepada saya selain kalimat pertamanya, “Tampangnya intelek, Semarang-Cirebon tiga ribu, bla bla bla” Yang bagian bla bla bla itu bisa Anda isi sendiri dengan aneka macam sumpah serapah. Itu terjadi di ruang terbuka, dalam jangkauan telinga para calon penumpang bus di ruang tunggu. Pokoknya dari tempat parkir bus ke ruang tunggu, kami dibentak-bentak dengan aneka macam khotbah, tapi ya itu tadi, yang mengesan dalam hati saya hanya kalimat pertama: tampang intelek, yang artinya “bego’ banget gak tau ongkos Semarang-Cirebon!”
[Memang sebagian orang mengira saya intelek, tapi jika itu benar pun, mungkin tidak dalam arti intelek yang dimaksudkannya]
Tak lama setelah kami ada di ruang tunggu, kami lihat bus yang tadi kami naiki itu berangkat, padahal setahu saya belum ada penumpangnya. Betul saja, tidak lama kemudian, bus itu kembali ke posisi parkir semula, dan saya ajak adik-adik saya naik lagi. “Itu tadi calo, Mas,” begitu kata sopir. Dalam hati saja saya bilang, “Calo teman kongkalikongmu toh!”
Teks Injil hari ini mungkin memakai istilah berbeda. Bukan “tampang intelek”, melainkan “bijaksana”, yang dilawankan dengan kata “bodoh”. Bagaimana membedakan gadis bodoh dan gadis bijaksana? Pasti bukang dari tampannya, juga bukun dari perilukunya. Lantas dari apanya? Saran teks bacaan hari ini: dari keawasannya, berjaga-jaganya, kesiapannya terhadap apa saja yang bisa terjadi kapan saja.
Bagaimana itu mungkin?
Ya mungkin banget, tinggal cari terjemahan tradisi rohani yang sudah disodorkan sejak zaman jebot: kualitas hidup yang dikonfirmasi oleh para nabi, penulis kebijaksanaan, dan seterusnya. Kualitas hidup ini bukan perkara ritual individualnya bagaimana, melainkan soal amal sosial yang menjadi rahmat bagi semesta dan bukan untuk kelompoknya sendiri.
Percaya atau tidak, itu bahkan bisa dipakai sebagai pedoman pemilu loh! Dalam kondisi flawed democracy, orang bijaksana memilih pemimpin yang track recordnya teruji, sekurang-kurangnya punya tradisi dengan ideologi terpuji. Perkara ini itu slenco, bertampang sombong atau lugu, itu ya seperti “tampang intelek” tadi. Orang bodoh akan memilih pemimpin yang pragmatis dengan dalih tidak ada kawan lawan yang tetap, yang dulu lawan bisa jadi kawan, dan sebaliknya. Ia tak bisa membedakan mana maling sesungguhnya karena semua berteriak maling, calo, koruptor, dan seterusnya.
Tuhan, mohon rahmat kebijaksanaan supaya kami senantiasa dapat menjalankan apa yang sungguh Kaukehendaki bagi kami. Amin.
HARI MINGGU BIASA XXXII A/1
12 November 2023
Keb 6,13-17
1Tes 4,13-18
Mat 25,1-13
Posting 2020: Hidup Sekali Ini
Posting 2017: Hai, Gadis Bodoh